Opini
Dari Ininnawa Ke Neurosains: Tafsir Manusia Dalam Lirik Lisan Bugis
Senin, 28 Jul 2025 17:14
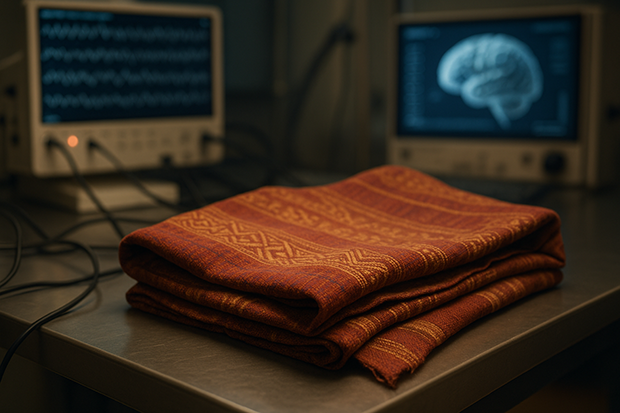
Ininnawa mungkin hanya terdengar seperti nyanyian lembut seorang ibu kepada anaknya. Tapi bait-baitnya mengandung lebih dari sekadar nasihat. Illustrasi: ChatGPT
Matahari belum jatuh, tapi sinarnya mulai melembut.
Angin menyusup pelan dari sela dinding rumah panggung,
membawa aroma padi yang menguning dan tanah yang mulai meretak.
Sebuah lantunan terdengar samar, tak utuh, namun seirama buaian sarung tua yang disematkan pada langit.
Nada-nadanya pelan, seperti jejak angin yang tergerus di permukaan air.
Tak menyampaikan wasiat, tak mewariskan materi, tapi cukup mengendapkan makna.
Bukan hanya makna, melainkan sebuah gagasan yang mungkin belum sempat dituliskan.
Lantunan Ininnawa.
Lagu ini mungkin hanya terdengar seperti nyanyian lembut seorang ibu kepada anaknya.
Tapi bait-baitnya mengandung lebih dari sekadar nasihat:
ia adalah jalan sunyi menuju pemahaman hakikat manusia.
"Dari jauh, kulihat engkau berjalan sendirian,
tapi sebenarnya engkau bertiga.
Aku pun juga bertiga.
Nyawaku, tubuhku, dan perbuatanku."
Di sinilah, nyanyian Bugis yang diwariskan dalam lontara bambu,
terpahat pertanyaan paling tua umat manusia:
apa dan siapa diri kita?
Lirik itu tidak menuntut untuk dijawab. Tapi ia membuka celah.
Bahwa manusia bukan satu. Bahwa yang terlihat bukan seluruhnya.
Bahwa dalam satu langkah, ada tiga dimensi yang turut berjalan: tubuh, jiwa, dan amal.
Tidak semua yang berjalan bersama bisa terlihat sekaligus.
Kadang, yang paling dekat justru yang paling luput disadari.
Seperti halnya lagu ini —
untuk memahaminya, kita harus kembali pada tanah yang melahirkannya.
"Kita menapak tanah yang melahirkannya."
Di tanah Bugis, manusia tidak dibaca hanya dari bentuknya, tapi dari apa yang menyertai langkahnya.
Bukan hanya tubuh yang dilihat, tapi juga nyawa yang menggerakkan, dan laku yang menegaskan.
Dalam kehidupan orang Bugis, ketiganya hadir bukan sebagai bagian yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan gerak.
Tubuh membawa nama,
jiwa membawa rasa,
dan perbuatan membawa harga.
Tubuh (tubuku) adalah yang tampak.
Ia bisa dilihat, disentuh, dikenali. Tapi dalam tradisi Bugis, tubuh tidak berdiri sendiri.
Tubuh adalah wadah kehormatan (siri’) — harga diri yang tak bisa dipermalukan tanpa melukai batin.
Ia dijaga bukan karena bentuknya, bukan pula karena tubuh itu indah,
tapi karena ia membawa martabat: rupa tau — rupa manusia.
Penjagaannya tampak dalam cara berpakaian, cara berdiri, bahkan dalam cara menerima tamu.
Jiwa (nyawaku) adalah yang menghidupkan.
Ia bukan sekadar napas kehidupan, tapi rasa yang mendalam.
Ia merasakan malu ketika salah, ikut sakit saat orang lain menderita — inilah yang disebut pacce.
Dalam kebudayaan Bugis, jiwa adalah pusat empati dan ketulusan.
Ia adalah kesadaran yang tahu kapan menunduk, dan tahu kapan bersikap tegas.
Ia bukan sekadar batin, tapi juga etika dan keberanian yang diam-diam menuntun laku.
Perbuatan (passengerengngede) adalah jejak.
Di sanalah tubuh dan jiwa bertemu: tempat ujian siri’ dan pacce yang terwujud dalam tindakan.
Sebab tubuh bisa tegap, dan jiwa bisa lembut — tapi tanpa laku yang benar, keduanya runtuh.
Bugis tidak mengenal seseorang dari nama atau asalnya, apalagi dari janjinya.
Tapi dari laku, dari apa yang ia tegakkan, dan bagaimana ia bertahan.
Seperti kata mereka: siri’na pacce, lempu na getteng —
kehormatan dan empati, kejujuran dan keteguhan.
Dalam tiga dimensi itu — tubuh, jiwa, dan amal —
manusia Bugis melangkah, berdiri, dan bertahan.
Ia tidak perlu menyebut ketiganya setiap waktu,
karena hidupnya sendiri adalah cara menyebut mereka sekaligus.
Jika Bugis menyanyikan diri dalam buaian,
maka Persia menemukannya dalam bara.
Di sini, tauhid tak hanya diajarkan, tapi ditempa.
Diuji di tengah gejolak cinta, pertarungan logika, dan silaunya cahaya.
Melahirkan tafsir yang tidak kaku, melainkan menyala.
Diri bukan lagi sekadar siapa aku,
tapi menjadi pertanyaan yang terbakar:
“Siapa yang Aku cintai?” dan “Siapa yang mencintaiku?”
Dari tungku Persia, membara Filsafat Islam.
Dalam Filsafat Islam, diri manusia dibaca dalam tiga lapisan:
tubuh, jiwa, dan amal.
Tubuh (Jism) adalah materi.
Ia bukan sekedar wujud, tapi lapisan dasar diri manusia.
Ia adalah pintu masuk ke dalam dunia inderawi, tempat segala pengetahuan pertama kali ditemukan.
Tubuh adalah wadah bagi jiwa, yang kelak akan mengaktualkan potensinya.
Namun tubuh bisa menjadi tirai — yang menutup cahaya atau memantulkannya.
Maka tubuh bukan musuh yang harus ditinggalkan,
tapi kendaraan yang dijaga, diarahkan, lalu dilepaskan —
bila waktunya tiba.
Jiwa (Nafs) adalah substansi.
Ia bukan sekadar napas atau getaran batin,
tetapi inti yang menghidupkan tubuh,
menggerakkan kehendak, dan menanggung kesadaran.
Ia menerima rangsangan dari tubuh,
lalu mengolahnya melalui daya ingat, imajinasi, dan penalaran.
Di sinilah manusia mulai menyadari:
bukan hanya “aku ada”, tapi juga “aku tahu aku ada.”
Namun jiwa juga tak tetap bentuknya.
Ia bisa ditarik ke bawah oleh hawa nafsu,
atau dituntun naik oleh cahaya pengetahuan.
Amal (Af‘al) adalah aktualisasi
Ia adalah cerminan tubuh dan jiwa —
tempat semua potensi menjadi nyata,
dan semua keyakinan diuji oleh perbuatan.
Amal bukan sekadar gerakan fisik,
tetapi wujud dari kehendak yang telah diarahkan.
Ia menunjukkan arah jiwa, dan memperlihatkan nilai tubuh.
Tanpa amal, tubuh hanya diam, dan jiwa hanya bayangan.
Setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran,
akan meninggalkan bekas: memperhalus atau mengeraskan.
Karena itu, amal bukan sekadar cermin dari dalam,
tapi juga alat pembentuk jiwa kembali.
Di tanah para penyair, sufi, dan pecinta —
tubuh, jiwa, dan amal bukan hanya dikenal,
tapi dijadikan jembatan menuju Yang Maha Esa.
Jika filsafat dan spiritualitas berangkat dari tanya dan perenungan,
maka neurosains masuk lewat observasi dan pengukuran.
Namun yang mereka cari — di ujungnya — bisa jadi sama:
apa itu diri?
dan bagaimana manusia menjadi sadar bahwa ia ada.
Dalam neurosains, tubuh bukan hanya lapisan, bukan pula sekedar bejana.
Ia adalah sistem biologis yang hidup, terhubung, belajar dan bereaksi.
Otak adalah pusat kendali, tapi kesadaran tidak berhenti di sana.
Ia didistribusikan di sumsum tulang belakang, di usus, di kulit, bahkan di otot.
Pikiran tak tinggal di kepala.
Ia menjalar ke seluruh tubuh, disimpan dalam otot, dikenang dalam detak jantung,
dan direspon saat pori-pori merasa takut: embodied-cognition.
Bahwa manusia berpikir dengan tubuhnya, bukan hanya dengan otaknya.
Gerakan, postur, bahkan cara berjalan —
ikut mempengaruhi cara kita merasa dan memaknai dunia.
Namun pikiran pun bukan cuma satu.
Ia terbagi dalam tiga poros yang saling menarik:
cognition yang berpikir,
emotion yang merasa,
dan conation yang mendorong untuk bertindak.
Tripartite-mind: tiga poros yang mengalir dalam napas neurosains dan psikologi.
Tiga daya yang hidup dalam satu tubuh,
namun tak selalu bersepakat.
Kadang cognition tahu apa yang benar,
tapi emotion menolak karena sakit.
Kadang conation ingin bergerak,
tapi tubuh justru diam dan beku.
Ada yang bergerak dalam dada, tetapi tak terbaca dalam kurva.
Meskipun dirasakan dalam gelombang yang nampak di layar,
tidak semuanya mampu terekam dan bisa dipetakan.
Neurophenomenology mencoba mengajak bicara.
Ia membuka ruang bagi rasa yang tak selesai dalam angka,
dan memberi tempat bagi makna yang lahir dari pengalaman.
Ia tak hanya membaca dari layar,
tapi juga mendengarkan dari dalam.
Memahami manusia dari luar sebagai objek ilmiah,
dan dari dalam sebagai subjek yang mengalami.
Lantunan ini telah dinyanyikan oleh banyak ibu — bahkan sebelum ibu itu sendiri mengenalnya.
Ia berpindah dari pangkuan ke pangkuan, dan dari suara ke suara.
Ia telah dinyanyikan, dan direkam dalam berbagai versi:
dari pita analog, hingga gelombang digital.
Kurva-kurva audionya mungkin telah dianalisis,
dipotong, dimastering, dan diunggah ke internet.
Namun tetap saja, ada sesuatu yang hilang dari setiap rekamannya:
getar dada yang hanya bisa datang dari ibu yang menyanyikannya.
Ininnawa memang ditemukan dalam ceropong bambu,
tapi dalam kerapuhannya, tertanam pertanyaan tua tentang manusia.
Ia tidak mengajukan definisi, tidak pula nampak di layar laboratorium,
melainkan melantunkan — bahwa manusia tak pernah berjalan sendiri.
"Nyawaku na tubuku
Alla passengerengngede."
Malam belum sepenuhnya turun, tapi senja sudah selesai menaruh warnanya.
Ia lepas dari buaian, lalu didekap dalam pelukan yang erat.
Karena esok hari, sang Ibu akan pergi.
Perjalanan jauh, suci, dan tak mudah.
Selesai.
Angin menyusup pelan dari sela dinding rumah panggung,
membawa aroma padi yang menguning dan tanah yang mulai meretak.
Sebuah lantunan terdengar samar, tak utuh, namun seirama buaian sarung tua yang disematkan pada langit.
Nada-nadanya pelan, seperti jejak angin yang tergerus di permukaan air.
Tak menyampaikan wasiat, tak mewariskan materi, tapi cukup mengendapkan makna.
Bukan hanya makna, melainkan sebuah gagasan yang mungkin belum sempat dituliskan.
Lantunan Ininnawa.
Lagu ini mungkin hanya terdengar seperti nyanyian lembut seorang ibu kepada anaknya.
Tapi bait-baitnya mengandung lebih dari sekadar nasihat:
ia adalah jalan sunyi menuju pemahaman hakikat manusia.
"Dari jauh, kulihat engkau berjalan sendirian,
tapi sebenarnya engkau bertiga.
Aku pun juga bertiga.
Nyawaku, tubuhku, dan perbuatanku."
Di sinilah, nyanyian Bugis yang diwariskan dalam lontara bambu,
terpahat pertanyaan paling tua umat manusia:
apa dan siapa diri kita?
Lirik itu tidak menuntut untuk dijawab. Tapi ia membuka celah.
Bahwa manusia bukan satu. Bahwa yang terlihat bukan seluruhnya.
Bahwa dalam satu langkah, ada tiga dimensi yang turut berjalan: tubuh, jiwa, dan amal.
Tidak semua yang berjalan bersama bisa terlihat sekaligus.
Kadang, yang paling dekat justru yang paling luput disadari.
Seperti halnya lagu ini —
untuk memahaminya, kita harus kembali pada tanah yang melahirkannya.
Ininnawa: Tafsir Bugis atas Diri
"Kita menapak tanah yang melahirkannya."
Di tanah Bugis, manusia tidak dibaca hanya dari bentuknya, tapi dari apa yang menyertai langkahnya.
Bukan hanya tubuh yang dilihat, tapi juga nyawa yang menggerakkan, dan laku yang menegaskan.
Dalam kehidupan orang Bugis, ketiganya hadir bukan sebagai bagian yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan gerak.
Tubuh membawa nama,
jiwa membawa rasa,
dan perbuatan membawa harga.
Tubuh (tubuku) adalah yang tampak.
Ia bisa dilihat, disentuh, dikenali. Tapi dalam tradisi Bugis, tubuh tidak berdiri sendiri.
Tubuh adalah wadah kehormatan (siri’) — harga diri yang tak bisa dipermalukan tanpa melukai batin.
Ia dijaga bukan karena bentuknya, bukan pula karena tubuh itu indah,
tapi karena ia membawa martabat: rupa tau — rupa manusia.
Penjagaannya tampak dalam cara berpakaian, cara berdiri, bahkan dalam cara menerima tamu.
Jiwa (nyawaku) adalah yang menghidupkan.
Ia bukan sekadar napas kehidupan, tapi rasa yang mendalam.
Ia merasakan malu ketika salah, ikut sakit saat orang lain menderita — inilah yang disebut pacce.
Dalam kebudayaan Bugis, jiwa adalah pusat empati dan ketulusan.
Ia adalah kesadaran yang tahu kapan menunduk, dan tahu kapan bersikap tegas.
Ia bukan sekadar batin, tapi juga etika dan keberanian yang diam-diam menuntun laku.
Perbuatan (passengerengngede) adalah jejak.
Di sanalah tubuh dan jiwa bertemu: tempat ujian siri’ dan pacce yang terwujud dalam tindakan.
Sebab tubuh bisa tegap, dan jiwa bisa lembut — tapi tanpa laku yang benar, keduanya runtuh.
Bugis tidak mengenal seseorang dari nama atau asalnya, apalagi dari janjinya.
Tapi dari laku, dari apa yang ia tegakkan, dan bagaimana ia bertahan.
Seperti kata mereka: siri’na pacce, lempu na getteng —
kehormatan dan empati, kejujuran dan keteguhan.
Dalam tiga dimensi itu — tubuh, jiwa, dan amal —
manusia Bugis melangkah, berdiri, dan bertahan.
Ia tidak perlu menyebut ketiganya setiap waktu,
karena hidupnya sendiri adalah cara menyebut mereka sekaligus.
Persia: Di Mana Api Membakar Tauhid
Jika Bugis menyanyikan diri dalam buaian,
maka Persia menemukannya dalam bara.
Di sini, tauhid tak hanya diajarkan, tapi ditempa.
Diuji di tengah gejolak cinta, pertarungan logika, dan silaunya cahaya.
Melahirkan tafsir yang tidak kaku, melainkan menyala.
Diri bukan lagi sekadar siapa aku,
tapi menjadi pertanyaan yang terbakar:
“Siapa yang Aku cintai?” dan “Siapa yang mencintaiku?”
Dari tungku Persia, membara Filsafat Islam.
Dalam Filsafat Islam, diri manusia dibaca dalam tiga lapisan:
tubuh, jiwa, dan amal.
Tubuh (Jism) adalah materi.
Ia bukan sekedar wujud, tapi lapisan dasar diri manusia.
Ia adalah pintu masuk ke dalam dunia inderawi, tempat segala pengetahuan pertama kali ditemukan.
Tubuh adalah wadah bagi jiwa, yang kelak akan mengaktualkan potensinya.
Namun tubuh bisa menjadi tirai — yang menutup cahaya atau memantulkannya.
Maka tubuh bukan musuh yang harus ditinggalkan,
tapi kendaraan yang dijaga, diarahkan, lalu dilepaskan —
bila waktunya tiba.
Jiwa (Nafs) adalah substansi.
Ia bukan sekadar napas atau getaran batin,
tetapi inti yang menghidupkan tubuh,
menggerakkan kehendak, dan menanggung kesadaran.
Ia menerima rangsangan dari tubuh,
lalu mengolahnya melalui daya ingat, imajinasi, dan penalaran.
Di sinilah manusia mulai menyadari:
bukan hanya “aku ada”, tapi juga “aku tahu aku ada.”
Namun jiwa juga tak tetap bentuknya.
Ia bisa ditarik ke bawah oleh hawa nafsu,
atau dituntun naik oleh cahaya pengetahuan.
Amal (Af‘al) adalah aktualisasi
Ia adalah cerminan tubuh dan jiwa —
tempat semua potensi menjadi nyata,
dan semua keyakinan diuji oleh perbuatan.
Amal bukan sekadar gerakan fisik,
tetapi wujud dari kehendak yang telah diarahkan.
Ia menunjukkan arah jiwa, dan memperlihatkan nilai tubuh.
Tanpa amal, tubuh hanya diam, dan jiwa hanya bayangan.
Setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran,
akan meninggalkan bekas: memperhalus atau mengeraskan.
Karena itu, amal bukan sekadar cermin dari dalam,
tapi juga alat pembentuk jiwa kembali.
Di tanah para penyair, sufi, dan pecinta —
tubuh, jiwa, dan amal bukan hanya dikenal,
tapi dijadikan jembatan menuju Yang Maha Esa.
Di Ruang Sunyi: Kurva Mengajak Bicara
Jika filsafat dan spiritualitas berangkat dari tanya dan perenungan,
maka neurosains masuk lewat observasi dan pengukuran.
Namun yang mereka cari — di ujungnya — bisa jadi sama:
apa itu diri?
dan bagaimana manusia menjadi sadar bahwa ia ada.
Dalam neurosains, tubuh bukan hanya lapisan, bukan pula sekedar bejana.
Ia adalah sistem biologis yang hidup, terhubung, belajar dan bereaksi.
Otak adalah pusat kendali, tapi kesadaran tidak berhenti di sana.
Ia didistribusikan di sumsum tulang belakang, di usus, di kulit, bahkan di otot.
Pikiran tak tinggal di kepala.
Ia menjalar ke seluruh tubuh, disimpan dalam otot, dikenang dalam detak jantung,
dan direspon saat pori-pori merasa takut: embodied-cognition.
Bahwa manusia berpikir dengan tubuhnya, bukan hanya dengan otaknya.
Gerakan, postur, bahkan cara berjalan —
ikut mempengaruhi cara kita merasa dan memaknai dunia.
Namun pikiran pun bukan cuma satu.
Ia terbagi dalam tiga poros yang saling menarik:
cognition yang berpikir,
emotion yang merasa,
dan conation yang mendorong untuk bertindak.
Tripartite-mind: tiga poros yang mengalir dalam napas neurosains dan psikologi.
Tiga daya yang hidup dalam satu tubuh,
namun tak selalu bersepakat.
Kadang cognition tahu apa yang benar,
tapi emotion menolak karena sakit.
Kadang conation ingin bergerak,
tapi tubuh justru diam dan beku.
Ada yang bergerak dalam dada, tetapi tak terbaca dalam kurva.
Meskipun dirasakan dalam gelombang yang nampak di layar,
tidak semuanya mampu terekam dan bisa dipetakan.
Neurophenomenology mencoba mengajak bicara.
Ia membuka ruang bagi rasa yang tak selesai dalam angka,
dan memberi tempat bagi makna yang lahir dari pengalaman.
Ia tak hanya membaca dari layar,
tapi juga mendengarkan dari dalam.
Memahami manusia dari luar sebagai objek ilmiah,
dan dari dalam sebagai subjek yang mengalami.
Nyanyian Ibu, Suara Hikmah
Lantunan ini telah dinyanyikan oleh banyak ibu — bahkan sebelum ibu itu sendiri mengenalnya.
Ia berpindah dari pangkuan ke pangkuan, dan dari suara ke suara.
Ia telah dinyanyikan, dan direkam dalam berbagai versi:
dari pita analog, hingga gelombang digital.
Kurva-kurva audionya mungkin telah dianalisis,
dipotong, dimastering, dan diunggah ke internet.
Namun tetap saja, ada sesuatu yang hilang dari setiap rekamannya:
getar dada yang hanya bisa datang dari ibu yang menyanyikannya.
Ininnawa memang ditemukan dalam ceropong bambu,
tapi dalam kerapuhannya, tertanam pertanyaan tua tentang manusia.
Ia tidak mengajukan definisi, tidak pula nampak di layar laboratorium,
melainkan melantunkan — bahwa manusia tak pernah berjalan sendiri.
"Nyawaku na tubuku
Alla passengerengngede."
Malam belum sepenuhnya turun, tapi senja sudah selesai menaruh warnanya.
Ia lepas dari buaian, lalu didekap dalam pelukan yang erat.
Karena esok hari, sang Ibu akan pergi.
Perjalanan jauh, suci, dan tak mudah.
Selesai.
Tulisan ini disusun sebagai sebuah esai reflektif yang menghubungkan lirik lisan Bugis Ininnawa dengan pendekatan filsafat dan neurosains. Penulis tidak bermaksud menetapkan satu tafsir tunggal, melainkan justru mengajak pembaca untuk membuka kembali pintu-pintu makna yang mungkin telah lama terlewati. Redaksi menerima tulisan ini dari seorang pembaca yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Tulisan telah disunting seperlunya untuk kepentingan keterbacaan.
(mhj)
Berita Terkait

News
Asyura di Dapur: Mengaduk Peca', Mengganti Pecah Belah
Tradisi Asyura di Sulawesi Selatan sarat makna: dari belanja pecah belah hingga mengaduk bubur, ritus dapur yang menyatukan spiritualitas, warisan lokal, dan kalender langit. Tak ada dalil, tapi ada peca’ — sebab dapur pun bisa jadi ruang ibadah.
Minggu, 06 Jul 2025 20:37

News
Sejjil: Dari Karbala Ke Lauh Mahfuzh
Rudal Sejjil bukan sekadar senjata Iran — ia memuat simbol wahyu, jejak Karbala, catatan Lauh Mahfuzh, dan makna tafsir militer dalam bahasa langit.
Minggu, 22 Jun 2025 06:22

News
Sinergi Budaya dan UMKM Perkuat Ekonomi Kreatif Daerah
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka secara resmi Phinisi Hospitality Fair (PHF) 2025 di Phinisi Point (Phipo) Mall Makassar, Jumat, (20/06/2025).
Sabtu, 21 Jun 2025 10:58

News
Akal Sehat: Jalan Menuju Tuhan ala Rocky Gerung
Menggali makna “akal sehat” Rocky Gerung sebagai jalan spiritual yang menolak dogma dan menegaskan tanggung jawab nalar dalam iman dan demokrasi.
Kamis, 12 Jun 2025 23:23

Sulsel
Membangun Kemajuan Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Cinta untuk Lansia
Di tanah yang subur bernama Bumi Batara Guru, jantung legenda dan kebanggaan Tana Luwu. Disinilah, narasi yang dikisahkan dan diwariskan turun-temurun melalui kitab terpanjang bernama La Galigo.
Senin, 21 Apr 2025 09:30
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PLN Pastikan Keandalan PLTU Palu-3 untuk Topang Listrik Sulawesi Tengah
2
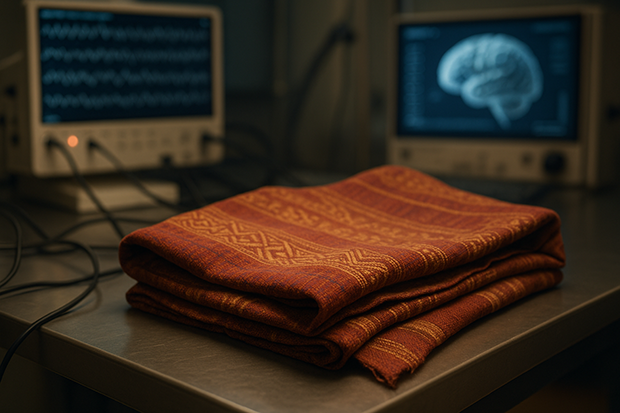
Dari Ininnawa Ke Neurosains: Tafsir Manusia Dalam Lirik Lisan Bugis
3

PB IPMIL RAYA Desak Polrestabes Makassar Tangkap Pelaku Teror dan Penyisiran Kampus
4

Munafri Bersama Kepala Daerah Luwu Raya dan Pihak Keamanan Cegah Konflik, Jaga Makassar Tetap Kondusif
5

Eks Ketua KONI Makassar Ahmad Sutanto Dituntut 6 Tahun Penjara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PLN Pastikan Keandalan PLTU Palu-3 untuk Topang Listrik Sulawesi Tengah
2
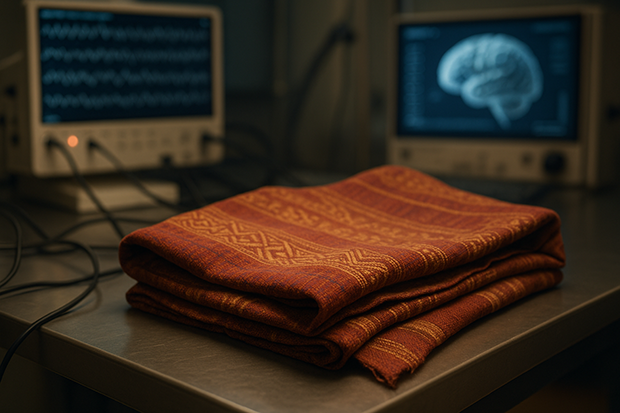
Dari Ininnawa Ke Neurosains: Tafsir Manusia Dalam Lirik Lisan Bugis
3

PB IPMIL RAYA Desak Polrestabes Makassar Tangkap Pelaku Teror dan Penyisiran Kampus
4

Munafri Bersama Kepala Daerah Luwu Raya dan Pihak Keamanan Cegah Konflik, Jaga Makassar Tetap Kondusif
5

Eks Ketua KONI Makassar Ahmad Sutanto Dituntut 6 Tahun Penjara

