OPINI: Korupsi, Amnesti, dan Abolisi
Senin, 04 Agu 2025 19:16

Prof Amir Ilyas, guru besar ilmu hukum Universitas Hasanuddin (Unhas). Foto: Dokumentasi pribadi
Oleh: Prof Amir Ilyas
Guru Besar Ilmu Hukum Unhas
SETELAH dua tokoh besar berentetan divonis bersalah pada Juli 2025 kemarin, Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto dalam dakwaan korupsi, masing-masing dengan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (merugikan keuangan negara) dan Pasal 5 ayat 1 (Suap) UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 (UU Tipikor). Tiba-tiba muncul berita yang mengejutkan, dengan melalui pengumuman secara terbuka dari Wakil Ketua DPR RI (Sufmi Dasco Ahmad), “DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto. Persetujuan tersebut berdasarkan Surat Presiden Nomor R-43/Pres/07025 bertanggal 30 Juli 2025 dan Surat Presiden Nomor R-42/Pres/072725 bertanggal 30 Juli 2025.”
Pertanyaan yang selanjutnya menyisakan ketidaktuntasan dari pelaksanaan “hak proregatif” Presiden tersebut, mengapa Tom Lembong diberikan abolisi, sementara Hasto diberikan amnesti? Apakah karena Tom Lembong sudah menyatakan pengajuan banding, sehingga lebih tepat mendapatkan abolisi, sebaliknya Hasto belum ada pernyataan banding, sehingga diberikan amnesti? Kalau hanya dengan alasan penghentian proses hukum yang sedang berjalan, tidakkah dalam kasus Hasto, JPU KPK sudah lebih duluan menyatakan banding atas vonis bersalah Sekjen PDIP itu, karena tidak menerima putusan tingkat pertama yang menyatakan perintangan penyidikan tidak terbukti untuknya.
Ataukah, karena dalam pandangan Presiden sebagai kepala negara, Tom Lembong bukan orang yang bersalah, sementara Hasto masih patut diberikan catatan “kesalahan”. Dugaan ini cukup beralasan untuk Hasto, karena saat yang sama salah satu komisioner KPK menyatakan, amnesti hanya dalam bentuk tidak melaksanakan hukuman saja, tetapi tetap saja bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Pro dan kontra mengenai penggunaan amnesti dan abolisi bukan hal baru. Dari orde lama, orde baru, era reformasi, hak prerogatif amnesti dan abolisi, bahkan sudah pernah digunakan oleh semua Presiden sesuai dengan masanya. Catatan besarnya, semua kasus yang pernah mendapatkan amnesti dan abolisi yakni terkait dengan delik makar yang dianggap dapat memecah belah negara (Kasus PRRI, DI/TII, Kasus Fretilin Timor Leste, Kasus GAM), sisanya ada kasus yang bernuansa politik (seperti kejahatan penghinaan terhadap martabat Presiden), ada pula kasus penghinaan melalui ITE (kasus Baiq Nuril 2021, di era Presiden Jokowi).
Seluruh UUD atau konstitusi yang pernah berlaku di negeri ini juga tidak eksplisit menyebutkan kapan amnesti dan abolisi bisa diberikan, apakah pemberiannya dengan permohonan atau langsung bisa diberikan oleh Presiden. Dari yang dahulunya hak prerogatif amnesti atau abolisi bersifat mutlak, kemudian perlahan dapat meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekarang dengan UUD NRI 1945 (hasil amandemen) dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Berdasarkan Pasal 4 UU Darurat RI No. 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Sedikit, ada gambaran untuk mendapatkan perbedaan penggunaan hak amnesti dan abolisi, amnesti berkonsekuensi terhapusnya akibat hukum pidana, sedangkan abolisi berkonsekuensi pada ditiadakannya penuntutan terhadap seseorang. Catatan atas UU tersebut, tidak lagi berlaku untuk sekarang, UU ini merupakan turunan dari Pasal 96 dan Pasal 107 UUDS RI, UU yang dibentuk dan berlaku sekali-selesai (einmahlig) atas kasus persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda 1949. Sehingga kurang tepat, bahkan keliru jika masih ada yang berpendapat untuk abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto, dalam hal ini Presiden juga perlu meminta nasehat dari Mahkamah Agung.
Dari sisi pemaknaan amnesti – amnestia – berarti “melupakan.” Melupakan pidana yang telah dilakukan, sehingga tidak perlu lagi dihukum (makanya akibat hukum pidananya berupa hukuman mati, penjara, denda, termasuk kalau ada hukuman tambahan, ditiadakan). Sedangkan abolisi – abolitio – berarti penghapusan. UU Darurat RI No. 11/1954 menekankan bahwa yang dihapus adalah tuntutan pidananya.
Amnesti seolah-olah nanti bisa berlaku jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hanya saja pemaknaan demikian, menjadi sulit lagi membedakannya dengan pemberian grasi, sebab grasi juga dimohonkan saat vonis dari putusan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, ada baiknya abolisi ini, bisa dimohonkan atau diberikan saat sudah ada putusan pengadilan tingkat pertama hingga putusan tingkat banding. Tentu dengan mengacu pada hakikat pemberian amnesti yakni melupakan tindak/perbuatan dari si petindak pidana (bukan pada meniadakan akibat pidananya). Sedangkan abolisi yang berarti meniadakan tuntutan pidana, pengajuan permohonan atau pemberiannya dapat diberikan saat perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh JPU. Atau kalau abolisi dipandang sebagai hak prerogatif Presiden menilai kinerja Aparat Penegak Hukum (Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum), dapat diperluas lagi pemberiannya saat seseorang sudah menyandang status tersangka.
Demi keadilan, demi penegakan hukum yang proporsional, nondiskrminatif, Presiden jangan terlalu mengobral “hak memberi amnesti dan hak memberi abolisi.” Apalagi berhubungan dengan kasus korupsi, selain KPK dan Kejaksaan akan buruk citra, pemberian hak demikan juga akan berpotensi “korupsi” dimaknai sebagai “delik politik” seperti kejahatan makar, leste majeste, sebagaimana kasus di masa lalu, seorang ditahan karena pesanan penguasa. Sekarang muncul syak wasangka, seorang menjadi tersangka korupsi oleh KPK, oleh JPU, karena pesanan siapa. Publik tahu dan lebih paham tentang itu.
Guru Besar Ilmu Hukum Unhas
SETELAH dua tokoh besar berentetan divonis bersalah pada Juli 2025 kemarin, Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto dalam dakwaan korupsi, masing-masing dengan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (merugikan keuangan negara) dan Pasal 5 ayat 1 (Suap) UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 (UU Tipikor). Tiba-tiba muncul berita yang mengejutkan, dengan melalui pengumuman secara terbuka dari Wakil Ketua DPR RI (Sufmi Dasco Ahmad), “DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto. Persetujuan tersebut berdasarkan Surat Presiden Nomor R-43/Pres/07025 bertanggal 30 Juli 2025 dan Surat Presiden Nomor R-42/Pres/072725 bertanggal 30 Juli 2025.”
Pertanyaan yang selanjutnya menyisakan ketidaktuntasan dari pelaksanaan “hak proregatif” Presiden tersebut, mengapa Tom Lembong diberikan abolisi, sementara Hasto diberikan amnesti? Apakah karena Tom Lembong sudah menyatakan pengajuan banding, sehingga lebih tepat mendapatkan abolisi, sebaliknya Hasto belum ada pernyataan banding, sehingga diberikan amnesti? Kalau hanya dengan alasan penghentian proses hukum yang sedang berjalan, tidakkah dalam kasus Hasto, JPU KPK sudah lebih duluan menyatakan banding atas vonis bersalah Sekjen PDIP itu, karena tidak menerima putusan tingkat pertama yang menyatakan perintangan penyidikan tidak terbukti untuknya.
Ataukah, karena dalam pandangan Presiden sebagai kepala negara, Tom Lembong bukan orang yang bersalah, sementara Hasto masih patut diberikan catatan “kesalahan”. Dugaan ini cukup beralasan untuk Hasto, karena saat yang sama salah satu komisioner KPK menyatakan, amnesti hanya dalam bentuk tidak melaksanakan hukuman saja, tetapi tetap saja bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Pro dan kontra mengenai penggunaan amnesti dan abolisi bukan hal baru. Dari orde lama, orde baru, era reformasi, hak prerogatif amnesti dan abolisi, bahkan sudah pernah digunakan oleh semua Presiden sesuai dengan masanya. Catatan besarnya, semua kasus yang pernah mendapatkan amnesti dan abolisi yakni terkait dengan delik makar yang dianggap dapat memecah belah negara (Kasus PRRI, DI/TII, Kasus Fretilin Timor Leste, Kasus GAM), sisanya ada kasus yang bernuansa politik (seperti kejahatan penghinaan terhadap martabat Presiden), ada pula kasus penghinaan melalui ITE (kasus Baiq Nuril 2021, di era Presiden Jokowi).
Seluruh UUD atau konstitusi yang pernah berlaku di negeri ini juga tidak eksplisit menyebutkan kapan amnesti dan abolisi bisa diberikan, apakah pemberiannya dengan permohonan atau langsung bisa diberikan oleh Presiden. Dari yang dahulunya hak prerogatif amnesti atau abolisi bersifat mutlak, kemudian perlahan dapat meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekarang dengan UUD NRI 1945 (hasil amandemen) dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Berdasarkan Pasal 4 UU Darurat RI No. 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Sedikit, ada gambaran untuk mendapatkan perbedaan penggunaan hak amnesti dan abolisi, amnesti berkonsekuensi terhapusnya akibat hukum pidana, sedangkan abolisi berkonsekuensi pada ditiadakannya penuntutan terhadap seseorang. Catatan atas UU tersebut, tidak lagi berlaku untuk sekarang, UU ini merupakan turunan dari Pasal 96 dan Pasal 107 UUDS RI, UU yang dibentuk dan berlaku sekali-selesai (einmahlig) atas kasus persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda 1949. Sehingga kurang tepat, bahkan keliru jika masih ada yang berpendapat untuk abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto, dalam hal ini Presiden juga perlu meminta nasehat dari Mahkamah Agung.
Dari sisi pemaknaan amnesti – amnestia – berarti “melupakan.” Melupakan pidana yang telah dilakukan, sehingga tidak perlu lagi dihukum (makanya akibat hukum pidananya berupa hukuman mati, penjara, denda, termasuk kalau ada hukuman tambahan, ditiadakan). Sedangkan abolisi – abolitio – berarti penghapusan. UU Darurat RI No. 11/1954 menekankan bahwa yang dihapus adalah tuntutan pidananya.
Amnesti seolah-olah nanti bisa berlaku jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hanya saja pemaknaan demikian, menjadi sulit lagi membedakannya dengan pemberian grasi, sebab grasi juga dimohonkan saat vonis dari putusan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, ada baiknya abolisi ini, bisa dimohonkan atau diberikan saat sudah ada putusan pengadilan tingkat pertama hingga putusan tingkat banding. Tentu dengan mengacu pada hakikat pemberian amnesti yakni melupakan tindak/perbuatan dari si petindak pidana (bukan pada meniadakan akibat pidananya). Sedangkan abolisi yang berarti meniadakan tuntutan pidana, pengajuan permohonan atau pemberiannya dapat diberikan saat perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh JPU. Atau kalau abolisi dipandang sebagai hak prerogatif Presiden menilai kinerja Aparat Penegak Hukum (Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum), dapat diperluas lagi pemberiannya saat seseorang sudah menyandang status tersangka.
Demi keadilan, demi penegakan hukum yang proporsional, nondiskrminatif, Presiden jangan terlalu mengobral “hak memberi amnesti dan hak memberi abolisi.” Apalagi berhubungan dengan kasus korupsi, selain KPK dan Kejaksaan akan buruk citra, pemberian hak demikan juga akan berpotensi “korupsi” dimaknai sebagai “delik politik” seperti kejahatan makar, leste majeste, sebagaimana kasus di masa lalu, seorang ditahan karena pesanan penguasa. Sekarang muncul syak wasangka, seorang menjadi tersangka korupsi oleh KPK, oleh JPU, karena pesanan siapa. Publik tahu dan lebih paham tentang itu.
(MAN)
Berita Terkait

News
In Memoriam Ismail Masse: Pelembagaan Demokrasi dan Integritas Penyelenggara Pemilu
Tulisan ini merupakan catatan singkat milik Syarifuddin Jurdi yang mengenang Ismail Masse, mantan Kabag SDM KPU Sulsel yang baru saja meninggal dunia.
Senin, 04 Agu 2025 14:07
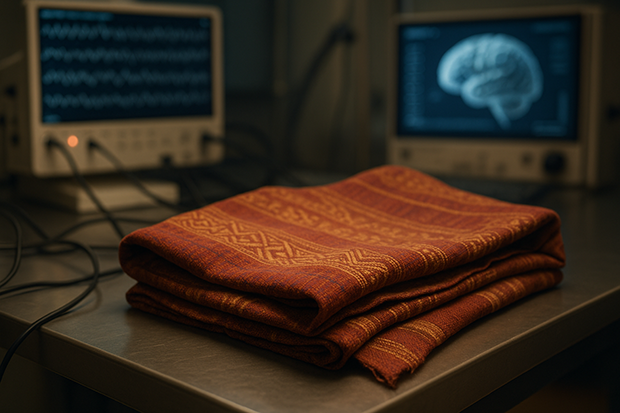
News
Dari Ininnawa Ke Neurosains: Tafsir Manusia Dalam Lirik Lisan Bugis
Dari buaian ibu Bugis hingga layar laboratorium, tulisan ini menelusuri tubuh, jiwa, dan amal manusia melalui lantunan Ininnawa, filsafat Persia, dan neurosains
Senin, 28 Jul 2025 17:14

News
Asyura di Dapur: Mengaduk Peca', Mengganti Pecah Belah
Tradisi Asyura di Sulawesi Selatan sarat makna: dari belanja pecah belah hingga mengaduk bubur, ritus dapur yang menyatukan spiritualitas, warisan lokal, dan kalender langit. Tak ada dalil, tapi ada peca’ — sebab dapur pun bisa jadi ruang ibadah.
Minggu, 06 Jul 2025 20:37

News
Sejjil: Dari Karbala Ke Lauh Mahfuzh
Rudal Sejjil bukan sekadar senjata Iran — ia memuat simbol wahyu, jejak Karbala, catatan Lauh Mahfuzh, dan makna tafsir militer dalam bahasa langit.
Minggu, 22 Jun 2025 06:22

News
Akal Sehat: Jalan Menuju Tuhan ala Rocky Gerung
Menggali makna “akal sehat” Rocky Gerung sebagai jalan spiritual yang menolak dogma dan menegaskan tanggung jawab nalar dalam iman dan demokrasi.
Kamis, 12 Jun 2025 23:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

In Memoriam Ismail Masse: Pelembagaan Demokrasi dan Integritas Penyelenggara Pemilu
2

Bendahara Golkar Sulsel Dukung Appi, Komitmen Tak Mau di Barisan Berseberangan
3

Fun Run 'Berlari ke Eropa': Berolahraga Sambil Wisata Keindahan Malino
4

KKN UIN Alauddin Posko 3 Gelar Seminar Kewirausahaan di Borongloe
5

OPINI: Korupsi, Amnesti, dan Abolisi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

In Memoriam Ismail Masse: Pelembagaan Demokrasi dan Integritas Penyelenggara Pemilu
2

Bendahara Golkar Sulsel Dukung Appi, Komitmen Tak Mau di Barisan Berseberangan
3

Fun Run 'Berlari ke Eropa': Berolahraga Sambil Wisata Keindahan Malino
4

KKN UIN Alauddin Posko 3 Gelar Seminar Kewirausahaan di Borongloe
5

OPINI: Korupsi, Amnesti, dan Abolisi

